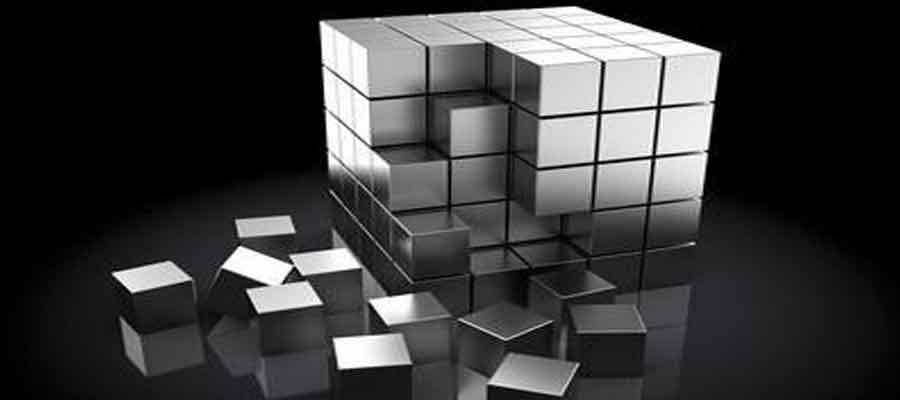Oleh: Mohammad Sabri
SETIAP sistem pemikiran, mengandaikan sesuatu yang tunggal, universal, dan total: menampik liyan, dan karena itu represif. Jacques Derrida menyebutnya “logosentrisme”. Dengan teknik yang pusparagam, ia mengguncang logosentrisme yang telah baku dalam pualam pemikiran Barat yang membentang sejak pra-Sokrates hingga Heidegger. Jika Nietzsche mewartakan “kematian Tuhan,” Derrida membisikkan ambang akhir “era ujaran” dan permulaan “era teks”. Palu godam yang ia pakai untuk merubuhkan bangunan lama adalah dekonstruksi.
Déconstruction, sebilah kata remeh dalam bahas Prancis, tapi punya makna magis di tangan Derrida. Dekonstruksi telah mengglobal dan memasuki berbagai bahasa. Kata yang tumbuh dari ladang filsafat Derrida ini telah menembus ke aneka teritori keilmuan: sastra, teologi, seni, arsitektur, politik, pendidikan, kritik musik dan film, sejarah, hukum hingga agama.
Dekonstruksi mewakili sebuah hasrat untuk membongkar bangunan yang telah mapan. Sebab itu, ia menjadi yel-yel bagi kelompok anti kemapanan. Tapi tak sedikit pula yang mencibirkannya. Gadamer, Frank, dan Habermas, adalah sederetan pemuka pemikir yang menciptakan badai kritik terhadap dekonstruksi. “Bagi saya dekonstruksi ini, bukan upaya intelektual serius. Éperons Derrida misalnya, tak lebih dari akrobat sastrawi yang tak terkait dengan soal kemanusiaan, religius, dan moral,” ungkap Gadamer.
Bagaimana dekonstruksi berlangsung dalam metafisika Barat yang logosentris? Begitu retorika Simon Critchley dan menjawabnya sendiri: “Pemikiran Derrida selalu merupakan pemikiran tentang sebuah teks dan dekonstruksi selalu terkait dengan pembacaan kritis atas teks.”
Derrida mendaku, “mendekonstruksi filsafat, berarti memikirkan genealogi terstruktur konsep-konsep filsafat.” Dalam sejarahnya, lanjut Derrida, filsafat lebih mengutamakan ucapan (voice) ketimbang tulisan (writing). “Sejarah metafisika, dengan segala dinamikanya, selalu menunjuk logos sebagai asal kebenaran yang terletak pada ujaran, bukan tulisan.” Logos adalah prinsip asali yang hadir pada dirinya sendiri, dalam arti filosofis pra-Sokratik. Inilah cara pandang nostalgia: di dalam logos, kebenaran hadir, di luar logos, tidak ada kebenaran dan makna.
Sepanjang sejarah logosentrisme, phoné (suara, ucapan) diyakini punya hubungan asali dengan logos atau pikiran. Manusia, karena itu, mengenal kebenaran dan makna yang berasal dari Logos Universal lewat pikiran, lalu orang mengenal isi pikiran lewat ucapan. Tapi dalam logosentrisme, jarak antara “logos-pikiran-ucapan” terabaikan. Ketiganya diyakini sebagai satu kesatuan. Argumennya: apabila seseorang berbicara, ia langsung mengatakan apa yang dipikirkannya. Itu sebabnya, ucapan dipandang sebagai sarana paling baik untuk menyampaikan kebenaran dan makna.
Bagaimana dengan teks? Teks lebih sebagai “suplemen” dan transkrip dari ucapan bagi seorang yang tidak hadir dalam percakapan. Sebagai transkrip, ia lebih “rendah” daripada percakapan. Tidak seperti percakapan, orang yang menulis butuh medium, yakni huruf-huruf. Karena itu pula, antara tulisan dan pikiran ada “jarak”. Itu sebabnya, tulisan kurang dipercaya sebagai penyeranta kebenaran dan makna. Di sini letak alasan, mengapa logosentrisme menjunjung ucapan dan merendahkan tulisan.
Bagi Derrida, logosentrisme berhasrat mengontrol kebenaran dan makna. Caranya, dengan megasalkan kebenaran dan makna pada “logos yang hadir” atau dalam arti sempit pada pembicara yang hadir. Di titik inilah Derrida membalik cara berpikir logosentrisme. Ketika Derrida mendekonstruksi tulisan Hegel, Derrida memperlihatkan bahwa bagi Hegel aspek audibel-temporal (fonetik-alfabet) dan visibel-spasial (nonfonetik) punya tempat masing-masing dan nilai yang setara. Namun, Hegel tetap mengandalkan tulisan alfabet. Semuanya berada dalam tradisi yang mengunggulkan ucapan daripada tulisan, sebab “ada” dimaknai sebagai kehadiran.
Heidegger yang berambisi merontokkan metafisika pun masih berupaya mendengarkan “suara-ada” (voice of being). Namun yang ia temukan adalah (sesuatu yang) diam, bisu, tanpa nada, tanpa kata, secara asali a-phonic. Pada Heidegger terjadi keretakan antara “makna asali ada” dan “kata”, antara “makna” dan “ucapakan”, antara “suara-ada” dan “phone”. Inilah yang disebut Derrida sebagai ambiguitas Heidegger dalam kaitannya dengan metafisika kehadiran dan logosentrisme.
Dalam Zur Seinsfrage, Heidegger memperbolehkan kata “ada” dibaca justru setelah kata ini dicoret. Namun, pencoretan ini bukan hanya simbol negatif, tapi merupakan tulisan terakhir dari sebuah zaman. Kehadiran tinanda transendental telah dihapus, tapi ia tetap terbaca. Dihapus, tapi tetap terbaca, dihancurkan sementara justru membuat tampak gagasan menjadi tanda. Gagasan mengenai tanda, ternyata diperoleh bukan lewat ucapan, tapi tulisan. Di sini, Derrida mengenalkan konsep tanda sebagai jejak, gram, atau différance. Dengan gagasan ini, tidak ada elemen tanda yang hadir dan mengacu pada dirinya sendiri; semuanya mengacu pada tanda lain yang berbeda dari dirinya dan tidak hadir. Tanda-tanda ini membentuk rantai, tenunan, yang diproduksi dari teks lain.
Begitulah, dengan mendekonstruksi logosentrisme, Derrida sejatinya, melanjutkan proyek Nietzsche dalam meradikalkan konsep penafsiran, perspektif, evaluasi, dan perbedaan. Bersama Nietzsche, Derrida membebaskan penanda dari ketergantungannya pada logos dan sebab itu, “kematian ujaran”: sebuah pengandaian nostalgia yang sejauh ini diyakini sebagai asal kebenaran. Di titik ini, era “teks” mekar dan bermula. (*)
* Direktur Pengkajian Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).